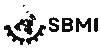Sumba, Nusa Tenggara Timur – Jika iklim adalah orang, mungkin ia sudah berteriak minta tolong sambil mengibarkan bendera putih. Sayangnya, teriakan itu sering tertutup suara mesin industri, proyek tambang, dan tepuk tangan para oligarki yang sibuk menghitung laba. Sementara di desa-desa, rakyat justru sibuk menghitung sisa hasil panen yang makin tipis, sebelum akhirnya mengemasi tas dan pergi menjadi buruh migran.
Fenomena ini disebut migrasi paksa, bukan karena masyarakat ingin jadi pahlawan devisa, tetapi karena hilangnya ruang hidup membuat bertahan di kampung halaman lebih mustahil daripada menunggu kebijakan pro-rakyat lahir dari langit.
SBMI: Migrasi Paksa untuk Bertahan Hidup
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat, krisis iklim telah mendorong banyak orang untuk bekerja ke luar negeri dengan cara yang tidak aman. Gagal panen bukan lagi hal baru bagi petani, laut tak lagi ramah bagi nelayan, dan bencana ekologis datang silih berganti, merampas ruang hidup golongan masyarakat yang paling rentan. Ini bukan migrasi biasa, masyarakat Indonesia terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Migrasi yang seharusnya adalah pilihan terbuka, menjadikan masyarakat kehilangan pilihan karena dampak bencana iklim.
Lebih ironis lagi, aktivis yang membela buruh migran kerap menghadapi gugatan balik alias SLAPP (Strategic Against Public Participation). SLAPP merupakan gugatan hukum yang digunakan untuk membungkam kritik dan aktivisme. “SLAPP menjadi alat yang korporasi dan negara untuk melemahkan pembela HAM, terutama kami yang memperjuangkan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta hak-hak buruh migran yang sering kali menjadi eksploitasi lintas sektor termasuk menjadi korban perdagangan orang yang strukturalnya terjadi karena migrasi menjadi sebuah keterpaksaan”, ujar Yunita Rohani Koordinator Departemen Pekerja Rumah Tangga SBMI dalam diskusi paralel di Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV.
WALHI: Daulat Rakyat, Bukan Daulat Oligarki
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai migrasi paksa hanyalah gejala dari persoalan yang lebih besar. Industrialisasi yang menghiraukan AMDAL, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada investor ketimbang warga desa.
Migrasi paksa ibaratnya hanyalah akibat dari melelehnya ujung gunung es. Selama oligarki menentukan arah pembangunan, rakyat akan terus kehilangan ruang hidupnya.
Solusi bukan hanya sekedar memperbaiki regulasi migrasi, melainkan meneguhkan daulat rakyat. Artinya, memberi kembali kendali kepada rakyat atas tanah, hutan, laut, dan sumber penghidupan mereka, bukan menyerahkannya ke meja rapat pemegang modal.
Mengejar Ikan dan Keberlangsungan Hidup
Kisah seorang nelayan lokal asal Sukabumi berinisial F pun sekaligus mantan Awak Kapal Perikanan (AKP) di Kapal berbendera Taiwan tahun 2014-2019. “Tangkapan ikan yang semakin berkurang, biaya melaut mahal, belum lagi membayar kebutuhan untuk melaut sehari-hari”, ujarnya. Alih-alih mendapatkan kehidupan yang layak saat menjadi AKP, F malah menjadi korban eksploitasi berulang.
Hal ini menggambarkan ironi, dimana rakyat harus memilih antara menunggu hasil laut yang tak bisa lagi memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup, atau menghadapi risiko kerja tanpa pelindungan di negeri orang.
Kebijakan yang Tak Pernah Berpihak
Krisis iklim membuka gerbang bahwa kebijakan negara sering lebih mesra dengan kepentingan industrialisasi besar ketimbang dengan nasib rakyat kecil. Dari tambang nikel di Sulawesi, geothermal di Nusa Tenggara Timur, hingga sawit di Kalimantan dan Papua, ruang hidup masyarakat tersapu proyek. Tak ada pilihan lain selain bermigrasi.
SBMI bersama jaringan di diskusi ini pun kompak menyerukan agar negara segera memperbaiki arah kebijakan, dengan menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, atur regulasi anti-SLAPP, dan pastikan pembangunan tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan oligarki semata.
Rekomendasi Panel 3: Hukum, HAM, dan Demokrasi – Pelindungan Pejuang HAM dan Lingkungan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme
Di tengah tekanan otoritarianisme, pelindungan bagi pejuang HAM dan lingkungan harus menyeluruh seperti dengan memperkuat regulasi dan hukum, memperluas pemahaman kriminalisasi termasuk SLAPP dan pelanggaran HAM berat, serta mengadopsi pendekatan inklusif yang memperhatikan gender, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Mekanisme praktis seperti database kasus, prosedur hukum khusus, pelatihan aparat, jaringan masyarakat sipil, dan peran media memastikan fakta lapangan terdengar dan kebenaran tidak tenggelam.
Di sisi politik, pelindungan membutuhkan komitmen pemerintah dan legislatif, uji awal perkara untuk mencegah kriminalisasi sejak awal, regulasi berbasis adat di tingkat daerah, serta pengakuan resmi pejuang HAM dan lingkungan sebagai subjek hukum yang sah, sehingga mereka benar-benar diakui dan terlindungi.
Penutup: Dari Migrasi ke Kedaulatan
Krisis iklim memang global, tapi dampaknya sangat lokal dan sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika laut menelan sawah, ketika tambang menyingkirkan hutan, rakyatlah yang lebih dulu kehilangan segalanya. Migrasi paksa hanyalah alarm keras yang menandakan ada yang salah dalam tata kelola negara.
SBMI dan WALHI mengingatkan: melindungi buruh migran sama pentingnya dengan mengembalikan kedaulatan rakyat atas ruang hidup. Tanpa itu, masyarakat akan terus terjebak pilihan sulit antara bertahan hidup atau meninggalkan kampung halaman, sementara di dalam negeri oligarki sibuk mengirim invoice.
Menegakkan hak rakyat berarti menghentikan kriminalisasi aktivis, menjadikan regulasi anti-SLAPP nyata, dan memastikan pembangunan berpihak pada kehidupan rakyat, bukan semata kepentingan modal. Lawan sekarang, atau tertindas selamanya.